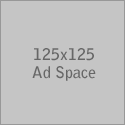"I'm not saying women are better. I've never said that. I'm saying we deserve some respect. More than Bobby Riggs or you are giving us." - Billy Jean King
Plot
Billy Jean King (Emma Stone) merupakan petenis perempuan yang mendominasi olahraga tersebut pada awal 70an. Tetapi baginya hal itu belumlah cukup, sebelum ia mendapatkan apa yang ia harapkan, yaitu persetaraan antara pria dan perempuan. Perjuangan itu pun tampaknya harus ia lakukan setelah Jack Kramer (Bill Pullman) mengadakan turnamen tenis dimana harga utama pria lebih tinggi 8 kali lipat dibandingkan perempuan. Jean memberontak, dan tidak bersedia untuk ikut turnamen tersebut. Ia lebih memilih untuk mengadakan turnamen dengan petenis-petenis perempuan lainnya, walaupun akhirnya ia harus menerima kenyataan jika ia dan kolega-kolega lainnya dikeluarkan dari organisasi tenis resmi yang diketuai oleh Jack. Namun, hal itu tetap tidak menghentikan Jean dalam memperjuangkan hak perempuan. Di tengah-tengah tur yang diadakan, Jean malah terlibat hubungan cinta terlarang antara dirinya dengan Marilyn (Andrea Riseborough). Hubungan ini tentu saja bisa mengancam karir, dan kehidupan keluarganya bersama sang suami, Larry (Austin Stowell). Di sisi lain, perjuangan Billy Jean menarik perhatian mantan petenis ternama, Bobby Riggs (Steve Carell) yang ingin segera menantang Billy Jean dalam permainan tenis dengan tujuan utama ingin membuktikan jika pria memang layak mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.
Review
Well, rasanya setelah menyaksikan film yang disutradarai oleh Jonathan Dayton dan Valerie Faries ini, tidak berlebihan jika saya menganggap Billy Jean King adalah Kartini-nya negara Amerika Serikat. Untuk generasi yang lahir di awal 90an, tentu saja nama Billy Jean King sangat asing untuk saya. Apalagi beliau merupakan atlit dari olahraga yang tidak terlalu saya ikuti. Sesuai judulnya, Battle of the Sexes mengambil plot utama dari perjuangan Billy Jean dalam mengupayakan hak perempuan supaya dapat disetarakan dengan kaum pria. Tetapi, Dayton-Valerie juga ikut memasukkan konflik-konflik kehidupan pula sebagai bumbu mengiringi perjuangan Billy Jean sebelum nanti di akhir film, ia akan berhadapan dengan Bobby Riggs dalam pertandingan yang diberi nama Battle of the Sexes. Disini, Billy Jean ditaruh sebagai protagonist utama berkat segala perjuangannya, namun sebagai seorang pria, jelas saja saya lebih memilih mendukung Billy Riggs. Apalagi kenyataannya sekarang, rasanya tuntutan untuk para perempuan dalam penyetaraan hak antara pria sudah sedikit berlebihan, dimana sekarang banyak sekali profesi-profesi pekerjaan yang diisi oleh perempuan.
Segala konflik yang menaungi kehidupan Billy Jean memang diperlukan untuk mengingatkan kepada penonton jika Billy Jean bukanlah sosok malaikat. Karena walaupun dirinya mungkin layak dianggap sebagai panutan dan pahlawan bagi para perempuan, dirinya tetaplah memiliki kekurangan akibat kelainan seks yang mengidap pada Billy Jean. Memanusiakan sosok Billy Jean inilah yang mungkin menjadi tujuan Dayton-Valerie sehingga mereka memfokuskan konflik ini pada 1 jam pertama, sebelum nanti 1 jam setelah nya, build up menuju pertandingan antara Jean vs Riggs mendominasi penceritaan.
Sebenarnya hal ini tidak lah salah, bahkan hal itu memang harus ada dalam sebuah biografi yang memiliki durasi yang tidak singkat. Penonton, terutama bagi yang mengenal atau bahkan mengidolai Billy Jean maupun Bobby Riggs, bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dan tentu juga lebih dalam lagi mengenal sosok Billy atau Bobby. Tetapi sayangnya, segala permasalahan pribadi Billy Jean kurang mampu mengikat untuk saya. Terbukti ketika film baru berdurasi 20 menit, saya merasakan film seolah telah berjalan 1 jam. Keinginan untuk menghentikan menonton film ini bisa saja saya lakukan apabila tidak ada adegan bercinta antara Billy dan Marilyn. Adegan yang dilakukan oleh dua aktris jelita tersebut pastinya sangat ampuh untuk menggoda saya untuk tetap menyaksikan film ini hingga akhir.
Sosok Billy Jean sendiri tidak terlalu menarik untuk saya. Padahal dengan segala sikapnya yang baik, memiliki paras yang cantik (karena diperankan oleh Emma Stone, tentu saja) dan posisinya sebagai rebel woman, seharusnya mudah untuk saya mendukung Billy Jean. Namun rupanya dengan segala atribut tersebut, tidak cukup menjadi alasan untuk saya menyukai Billy Jean. Bahkan pada momen terakhirnya yang seharusnya menjadi momen emosional bagi penonton (terutama para perempuan), saya tidak merasakan apapun, bahkan ada sedikit kekecewaan yang timbul melihat itu.
Dan kalau boleh jujur, saya lebih tertarik untuk mengenal sosok Bobby Riggs yang katanya kontroversial itu. Ya, kepribadian Bobby jelas jauh lebih compelling dibandingkan Billy Jean. Bobby merupakan pria yang karismatik dengan kemampuan bicaranya yang memiliki magnet tersendiri, namun selain itu ia juga merupakan gamble addicted, dan memiliki hubungan yang tidak terlalu baik dengan sang istri, Priscilla (Elizabeth Shue) dan anaknya, Larry (Lewis Pullman). Bahkan pada kehidupan Bobby pun terjadi ironi tersendiri. Dirinya menentang keinginan Billy Jean supaya perempuan bisa equal dengan kaum pria, tetapi disisi lain, kehidupan Bobby Riggs malah didominasi secara tidak langsung oleh istrinya sendiri. Sub plot ini bagi saya bisa lebih mengikat andai saja Bobby Riggs menjadi main focus nya disini. Tetapi karena film ini menceritakan sosok Billy Jean, maka sub plot dari Bobby Riggs hanya tampil di permukaan saja karena tidak ada waktu untuk mengeksplorenya lebih lanjut.
Steve Carell patut diberikan apresiasi akibat penampilan memikatnya sebagai Bobby Riggs. Tidak hanya memiliki muka yang begitu mirip dengan Bobby Riggs yang asli, namun Carell berhasil membuat sosok Bobby Riggs mudah disukai dengan segala flaws yang Bobby miliki. Bahkan ada satu momen yang berhasil membuat hati saya tersentuh berkat ekspresi yang dimainkan oleh Carell. Emma Stone juga tidak kalah cemerlangnya dengan membuat sosok Billy Jean lebih mudah menuai simpati dengan segala problematika yang melingkarinya. Kredit lebih juga harus kita berikan kepada Stone dan Carell yang mampu memainkan permainan tenis dengan baik sehingga terlihat mereka memang atlet yang sesungguhnya.
Battle of the Sexes mengambil penceritaan pada medio awal 70-an, dan mungkin memang pada periode itu, penyetaraan gender masih terlihat mimpi untuk para perempuan sehingga andai saja film ini hadir lebih awal, seperti 10-15 tahun sebelumnya, film ini masih lah relevan. However, Fast forward to present day, well, everything is change. Untuk kalian yang sedang mencari pekerjaan, tentu kalian menyadari jika saat ini dunia kerja tengah sedikit didominasi oleh perempuan, baik dari low level hingga pada top level management. Bahkan pada lowongan kerja, banyak sekali lowongan untuk para perempuan sehingga membuat perempuan lebih tinggi persentase mereka untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan para pria. Saya tidaklah menentang penyetaraan gender, bahkan saya pun merasa pernyataan Bobby Riggs dalam film ini yang menyatakan jika perempuan hanya ahli di ranjang dan dapur itu sangat merendahkan nilai perempuan. Tetapi bukan berarti pula keinginan perempuan untuk tidak terus berada di bayang-bayang laki-laki malah berubah seolah mereka menjadi pemimpin saat ini. Kenyataan yang terjadi di periode sekarang lah yang membuat saya tidak terlalu mendukung segala perjuangan Billy Jean (apalagi pada narasi terakhrinya, Billy Jean juga merupakan tokoh perjuangan pro LGBT. Well, Billy, how about no, please?). Dari segala kenyataan ini lah rasanya, film biografi yang sebenarnya berfungsi mengingatkan kita betapa pentingnya penyetaraan gender ini tidaklah terlalu relevan lagi, dan hal ini pula yang menjadi alasan mengapa saya tidak terlalu tersentuh ataupun merasa perlu mendukung sosok Billy Jean dalam film ini.