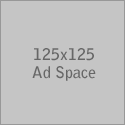Oh boy, what an interesting story we got here. Cerita yang begitu menarik sehingga mampu memaksa saya yang pemalas ini rela untuk membuat suatu tulisan untuk film yang bahkan belum dirilis. Kalau Anda mengikuti perkembangan dari film superhero wanita pertama dari MCU ini, Anda pasti telah mengetahui berbagai kontroversi yang mengitari Captain Marvel sehingga melahirkan backlash dari kalangan penggemar MCU sendiri. Dari trailer-trailer nya yang dinilai kurang meyakinkan, aroma propaganda SJW, fans yang menolak bila nanti Captain Marvel lah yang diisukan merupakan pahlawan yang menyelamatkan The Avengers dan mampu mengalahkan Thanos, hingga yang paling mengganggu fans adalah pernyataan kontroversi dari pemeran Captain Marvel itu sendiri, Brie Larson. Dan yang terbaru adalah situs Rotten Tomatoes memutuskan untuk menghilangkan skor "Want to see" di website tersebut.
Saya merupakan tipe penonton yang tidak terlalu mengandalkan sebuah trailer untuk mematok sebuah ekspektasi. Kecuali trailer Super Bowl dari Captain Marvel yang cringeworth tersebut, saya tidak terlalu mempermasalahkan trailer-trailer nya yang lain. Betul memang bila dari trailer tersebut kita belum bisa menebak sepenuhnya narasi dari Captain Marvel. Tetapi akan menjadi tindakan teledor pula menurut saya jika pihak Marvel memberikan clue yang banyak di dalam trailer nya. Saya masih ingat bagaimana geramnya saya atas kebodohan pihak Warner Bros atau DC yang menghadirkan sosok Wonder Woman pada trailer film Batman V Superman. Para fans juga mengkritik (atau lebih tepatnya khawatir) akan kapabilitas akting dari Brie Larson yang minim ekspresi pada trailer nya hingga ada yang membandingkan dirinya dengan karakter Bella Swan dari Twilight franchise. Dan disini saya juga kurang sependapat dan sepenuhnya masih mempercayai bila Brie Larson akan memberikan penampilan yang prima nantinya. Kapabilitas akting Brie Larson bagi saya cukup mumpuni, hell, she's already got an Oscar on her pocket. Lihatlah bagaimana meyakinkannya dia memerankan seorang ibu yang hopeless juga depresif pada film Room (2015).
Namun rasa optimis saya mulai memudar kala muncul rumor jika Captain Marvel akan dijadikan kampanye isu politik dari pihak SJW dan ingin menjadikan sosok Captain Marvel adalah ikon dari feminis. Dan isu inilah yang berhasil membuat saya mulai ragu apakah saya masih bisa menyukai film ini atau tidak nanti. Tampaknya pihak Disney masih belum belajar dari bagaimana para fans Star Wars yang sangat kecewa akan hasil akhir dari The Last Jedi maupun Solo. Pihak Disney masih juga belum menyadari jika para fans sama sekali tidak ingin franchise kesayangan mereka dilibatkan dalam politik SJW.
Franchise MCU memang tidaklah setua Star Wars, namun lebih dari satu dekade semenjak Iron Man dirilis, franchise ini berhasil melahirkan para fans yang loyal dan mencintai MCU. Para fans begitu perduli pada karakter-karakter nya, bahkan hingga karakter minor seperti Ned, Maria Hill dan tentunya Phil Coulson. Selain itu, Marvel juga berhasil menaikkan derajat superhero mereka seperti Ant-Man, Dr. Strange, dan The Guardians of the Galaxy. Bayangkan saja, sebuah franchise yang dibangun perlahan namun meyakinkan dengan karakter-karakter yang dicintai di dalamnya, harus tercoreng akibat kepentingan politik semata. Bayangkan rasa kesal nan kecewa yang harus dirasakan para penggemar MCU.
Kondisi yang sudah tidak mengenakkan ini, diperparah pula akan pernyataan-pernyataan tidak penting dari Brie Larson. Sudah bukan rahasia umum lagi bila Brie Larson adalah salah satu "agen" feminis layaknya Amy Schumer, tapi apakah begitu sulitnya untuk menahan pandangan idealisme pribadi terlebih dahulu setidaknya sampai filmnya benar-benar dirilis nanti? Bukan langkah yang bijak tentu saja mengeluarkan komentar berbau diskriminasi nan sexist sebelum film yang dibintangi bahkan belum menghiasi layar-layar bioskop. Tentu saja para penggemar semakin antipati akan sosok Brie Larson. Antipati yang dikhawatirkan akan menghasilkan ketidak sukaan juga terhadap karakter yang diperankan. Andai nanti hasil pendapatan Captain Marvel dibawah ekspektasi (I doubt it, though), maka tidak salah jika Brie Larson menjadi faktor utama.
Hingga yang menjadi perbincangan hangat dalam satu minggu terakhir adalah rating "Want to see" di website Rotten Tomatoes dihilangkan. Terakhir kali, sebelum pembaharuan, skor persentase Want to see untuk film Captain Marvel anjlok hingga 27%!!! "Loh, terus kenapa? Bukan masalah besar kan. Toh, film nya belum keluar. Gw yakin filmnya masih banyak ditonton. Skor "Want to see" mah gak terlalu penting." Benar, skor tersebut bukanlah patokan kuat apakah nanti film ini sukses atau tidak dari segi finansial. Namun, sekali lagi, Captain Marvel bukanlah film sembarangan. Film ini adalah bagian dari MCU, salah satu franchise tersukses dalam satu dekade belakangan. Film yang diharapkan menjadi simbol feminis bagi sebagian orang. Film ini diakuisisi oleh Disney, salah satu studio film terbesar sepanjang masa. Tentunya dengan kenyataan tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan.
Penghapusan skor "Want to see" ini dianggap oleh sebagian kalangan penggemar merupakan sebuah langkah desperate untuk "menyelamatkan" citra film Captain Marvel. Tidak hanya itu, langkah ini semakin menguatkan dugaan jika situs Rotten Tomatoes selama ini menganak emaskan film-film keluaran MCU atau dari Disney. Sudah banyak yang mengkritik situs ini dalam pemberian rating nya yang selalu tinggi untuk film-film dari MCU. Kritikus dianggap terlalu jinak pada film-film MCU. Contoh terkuat silahkan lihat begitu tingginya rating yang diterima Thor Ragnarok dan Black Panther yang dirasa tidak terlalu spesial. Awalnya dugaan konspirasi ini terkesan membual dan sekilas hanyalah pernyataan butthurt dari pihak oposisi Marvel (Baca: Fans DCEU). Namun dengan adanya pengupdatean ini, mau tidak mau, dugaan tersebut menguat dan bisa jadi adalah kebenaran. Pihak MCU belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Semua film MCU sebelumnya begitu dinantikan, termasuk Captain Marvel bahkan. Maka ketika ada satu film yang untuk pertama kalinya mendapatkan backlash luar biasa seperti ini, terlihat sekali jika pihak Marvel atau Disney mencoba melakukan segala cara untuk mempertahankan reputasi MCU. Sebuah keputusan yang seolah menyiramkan bensin di tengah kobaran api.
Segala kejadian tidak mengenakkan yang mengitari Captain Marvel ini jelas sekali menjadi hembusan angin segar untuk DC. Bila DC mampu memanfaatkan situasi ini, bukan tidak mungkin film bertemakan superhero yang selama ini dikuasai oleh Marvel, berpindah tangan ke pihak DC. Terlebih film rilisan DC, Aquaman (2018), cukup mendapatkan tanggapan positif baik dari segi kualitas maupun finansial. Bukan tidak mungkin ini adalah awal dari runtuhnya kedigdayaan MCU. Lalu pertanyaannya, apakah saya tetap akan menonton film ini? Kemungkinan besar, iya. Karena harus diakui, film Captain Marvel memiliki poin penting untuk film The Avengers selanjutnya, Endgame. Saya hanya berharap, dengan adanya backlash seperti ini, mampu menyadarkan pihak Disney jika para penggemar sama sekali tidak perduli akan agenda politik yang mereka simpan, dan juga tidak rela jika franchise kesayangan mereka dijadikan sebagai wadah propaganda politik SJW.