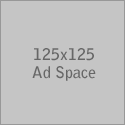Telah berselang kurang lebih 24 jam beranjak dari perhelatan Oscar kemarin dan perbincangan mengenai kontroversi yang ada tampaknya belum mereda. Yap, seperti yg kita ketahui bersama bahwa terjadi sebuah insiden yang bisa dibilang sangat memalukan dan mencoreng nama-nama pihak yang terlibat dimana pada momen pengumuman di kategori yang bisa dikatakan paling prestisius di ajang Oscar, yaitu Best Picture, Faye Dunaway dan Warren Beaty melakukan kesalahan dalam mengumumkan pemenang di kategori tersebut. Dunaway dan Beaty mengumumkan bila film La La Land lah yang berhasil menjadi pemenang dan berhak membawa piala patung emas. Namun beberapa menit kemudian, terungkap lah twist yang membuat para penonton terhenyak, yaitu pemenang sesungguhnya adalah Moonlight.
"This is not a joke. "Moonlight", has won Best Picture", ucap sang produser La La Land, Jordan Horowitz seraya memperlihatkan kertas yang bertuliskan Moonlight untuk meyakinkan apa yang ia ucapkan memang bukan candaan. Namun jelas, setelah apa yang terjadi, butuh beberapa menit untuk semua yang hadir sadar apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan semua pihak yang terlibat akan film Moonlight, terutama sang sutradara Barry Jenkins tampak berat untuk naik ke atas panggung. Jimmy Kimmel selaku host Oscar tahun ini pun mencoba menghangatkan suasana dengan melontarkan candaan-candaan di tengah situasi yang canggung itu. Warren Beaty yang sadar akan kekeliruannya menjelaskan dimana sebenarnya ia memang tidak yakin dengan amplop yang ia dan Faye pegang. Memang, detik-detik sebelum membacakan pengumuman, Warren memperlihatkan keraguan dalam membacakan nama judul film pemenang, sebelum Faye yang tampak yakin meneriakkan film La La Land. Semua kejadian ini memang sulit dipercayai, bahkan tidak sedikit yang mengira bila ini adalah kejadian yang telah direncanakan atau sebuah gimmick untuk film La La Land yang memiliki ending bittersweet. Namun setelah membacs beberapa artikel, tamoaknya situasi ini memang kecelakaan yang tak terduga.
Saya sendiri baru semalam melihat tayangan videonya (saya hanya memantau lewat live tweet), dan oh boy, trust me, it's so painful to watch. Saya sangat bersimpati dengan para kru atau aktor/artis yang terlibat akan film La La Land, yang bahkan perwakilan mereka telah menyampaikan speech nya di atas panggung. Raut kekecewaan diusahakan untuk tidak mereka tampakkan, bahkan sang sutradara pemenang Best Director, Damien Chazelle tak bisa menutupi ekspresi kecewanya kemarin. Kudos layak diberikan kepada Jordan Horowitz yang tampak jumawa akan pelakuan yang memalukan tersebut. Kejadian ini juga berpengaruh kepada sang pemenang, Moonlight. Tidak hanya Moonlight seakan menjadi kambing hitam akan kekalahan La La Land (bahkan berkomentar rasis mengenai film Moonlight), tapi kemenangan ini pastinya akan selalu dibayangi oleh insiden memalukan ini.
Saya memang menyukai twist ini karena memang bagi saya, Moonlight jauh lebih pantas mendapatkan penghargaan Best Picture. Dinamika emosi yang ada, sinematografi yang indah, statusnya sebagai film indie dengsn budget yang sangat minim dibandingkan kandidat-kandidat lainnya, membuat saya mendukung Moonlight selain film Arrival. Dua film tersebut murni instant classic. Namun dengan kemenangan seperti ini, saya takut akan tercipta backlash tersendiri akan film Moonlight, terutama dari pecinta film La La Land. Perlu diketahui, speech dari perwakilan Moonlight menghormati semua kru dari La La Land. Hal itu patut diberikan kredit tersendiri. Bahkan pemenang Best Supporting Actor, Mahershala Ali pun tidak terlalu tampak bahagia kala di atas panggung dalam rangka merayakan kemenangan setelah situasi super canggung itu. Dan untuk menenangkan para #TeamLaLaLand , ketahuilah bahwa La La Land adalah film yang mungkin paling rewatchable dibanding kandidat lainnya. Bahkan tanpa adanya situasi ini pun saya yakin, La La Land tetaplah film yang sulit untuk dilupakan.
Dan untuk semuah pihak yang terlibat dengan gelaran Oscar ini tentu sangatlah tercoreng namanya, terutama PwC (PricewaterhouseCoopers) yang bertanggung jawab dalam amplop pemenang tiap kategori. Pihak PwC oun telah meminta maaf akan blunder terburuk dalam sejarah Oscar ini. Banyak juga yang menyalahkan Faye Dunaway dan Warren Beaty dengan mempertanyakan kredibilitas mereka, walau memang insiden ini tidak pantas untuk disalahkan kepada mereka. Yah, walau bagaimanapun, bencana ini sulit untuk terlupakan dan akan selalu terkenang dalam beberapa periode mendatang.
Sebenarnya bukan ini saja blunder yang terjadi dalam pagelaran Oscar kemarin. Selain ini, ada juga kejadian yang akan selalu terkenang oleh Jan Chapman, produser dari Australia. Bagaimana tidak, saat momen untuk mengenang kepergian sang costume designer, Janet Patterson, muka yang ada di layar malah muka dari Jan Chapman. Bayangkan saja betapa shock nya Chapman akan tindakan memalukan ini. Bisa mengrrti bila Chapman sangat kecewa akan blunder ini. Taoi Chapman tidak perlu kuatir karena blunder ini tentu tidak akan terlalu diingat dibanding tragedi yang terjadi setelahnya. Dan ya, pihak Suicide Squad dan Steve Harvey merupakan orang yang paling bahagia sekarang.
"This is not a joke. "Moonlight", has won Best Picture", ucap sang produser La La Land, Jordan Horowitz seraya memperlihatkan kertas yang bertuliskan Moonlight untuk meyakinkan apa yang ia ucapkan memang bukan candaan. Namun jelas, setelah apa yang terjadi, butuh beberapa menit untuk semua yang hadir sadar apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan semua pihak yang terlibat akan film Moonlight, terutama sang sutradara Barry Jenkins tampak berat untuk naik ke atas panggung. Jimmy Kimmel selaku host Oscar tahun ini pun mencoba menghangatkan suasana dengan melontarkan candaan-candaan di tengah situasi yang canggung itu. Warren Beaty yang sadar akan kekeliruannya menjelaskan dimana sebenarnya ia memang tidak yakin dengan amplop yang ia dan Faye pegang. Memang, detik-detik sebelum membacakan pengumuman, Warren memperlihatkan keraguan dalam membacakan nama judul film pemenang, sebelum Faye yang tampak yakin meneriakkan film La La Land. Semua kejadian ini memang sulit dipercayai, bahkan tidak sedikit yang mengira bila ini adalah kejadian yang telah direncanakan atau sebuah gimmick untuk film La La Land yang memiliki ending bittersweet. Namun setelah membacs beberapa artikel, tamoaknya situasi ini memang kecelakaan yang tak terduga.
Saya sendiri baru semalam melihat tayangan videonya (saya hanya memantau lewat live tweet), dan oh boy, trust me, it's so painful to watch. Saya sangat bersimpati dengan para kru atau aktor/artis yang terlibat akan film La La Land, yang bahkan perwakilan mereka telah menyampaikan speech nya di atas panggung. Raut kekecewaan diusahakan untuk tidak mereka tampakkan, bahkan sang sutradara pemenang Best Director, Damien Chazelle tak bisa menutupi ekspresi kecewanya kemarin. Kudos layak diberikan kepada Jordan Horowitz yang tampak jumawa akan pelakuan yang memalukan tersebut. Kejadian ini juga berpengaruh kepada sang pemenang, Moonlight. Tidak hanya Moonlight seakan menjadi kambing hitam akan kekalahan La La Land (bahkan berkomentar rasis mengenai film Moonlight), tapi kemenangan ini pastinya akan selalu dibayangi oleh insiden memalukan ini.
Saya memang menyukai twist ini karena memang bagi saya, Moonlight jauh lebih pantas mendapatkan penghargaan Best Picture. Dinamika emosi yang ada, sinematografi yang indah, statusnya sebagai film indie dengsn budget yang sangat minim dibandingkan kandidat-kandidat lainnya, membuat saya mendukung Moonlight selain film Arrival. Dua film tersebut murni instant classic. Namun dengan kemenangan seperti ini, saya takut akan tercipta backlash tersendiri akan film Moonlight, terutama dari pecinta film La La Land. Perlu diketahui, speech dari perwakilan Moonlight menghormati semua kru dari La La Land. Hal itu patut diberikan kredit tersendiri. Bahkan pemenang Best Supporting Actor, Mahershala Ali pun tidak terlalu tampak bahagia kala di atas panggung dalam rangka merayakan kemenangan setelah situasi super canggung itu. Dan untuk menenangkan para #TeamLaLaLand , ketahuilah bahwa La La Land adalah film yang mungkin paling rewatchable dibanding kandidat lainnya. Bahkan tanpa adanya situasi ini pun saya yakin, La La Land tetaplah film yang sulit untuk dilupakan.
Dan untuk semuah pihak yang terlibat dengan gelaran Oscar ini tentu sangatlah tercoreng namanya, terutama PwC (PricewaterhouseCoopers) yang bertanggung jawab dalam amplop pemenang tiap kategori. Pihak PwC oun telah meminta maaf akan blunder terburuk dalam sejarah Oscar ini. Banyak juga yang menyalahkan Faye Dunaway dan Warren Beaty dengan mempertanyakan kredibilitas mereka, walau memang insiden ini tidak pantas untuk disalahkan kepada mereka. Yah, walau bagaimanapun, bencana ini sulit untuk terlupakan dan akan selalu terkenang dalam beberapa periode mendatang.
Sebenarnya bukan ini saja blunder yang terjadi dalam pagelaran Oscar kemarin. Selain ini, ada juga kejadian yang akan selalu terkenang oleh Jan Chapman, produser dari Australia. Bagaimana tidak, saat momen untuk mengenang kepergian sang costume designer, Janet Patterson, muka yang ada di layar malah muka dari Jan Chapman. Bayangkan saja betapa shock nya Chapman akan tindakan memalukan ini. Bisa mengrrti bila Chapman sangat kecewa akan blunder ini. Taoi Chapman tidak perlu kuatir karena blunder ini tentu tidak akan terlalu diingat dibanding tragedi yang terjadi setelahnya. Dan ya, pihak Suicide Squad dan Steve Harvey merupakan orang yang paling bahagia sekarang.