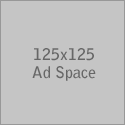"Listen to me, we're going on a trip now, it's going to be rough."- Malorie
Plot
Virus misterius yang menyerang seluruh dunia, termasuk negeri Amerika (tentu saja) mengakibatkan Malorie (Sandra Bullock) terjebak di dalam rumah, bersama orang-orang lainnya yang secara beruntung belum ikut terkena virus tersebut, salah satunya adalah Tom (Trevante Rhodes) yang menyelamatkan Malorie. Virus yang tersebar itu memberikan gejala ke siapapun yang terkena melalui kontak mata untuk melakukan tindakan membunuh dirinya sendiri.
Review
Film yang diadaptasi dari novel Josh Malerman dengan judul yang sama ini segera saja menjadi sebuah pop culture tersendiri berkat berpuluh gambar meme yang tersebar di internet. Konsep cerita nya memang tidak sepenuhnya original karena di tahun yang sama kita telah dihadiri A Quiet Place yang sama-sama memiliki genre horror. Bila pada film John Krasinki tersebut ancaman akan hadir bila para karakternya mengeluarkan suara sekecil apapun, karakter-karakter yang terlibat dalam Bird Box harus dipaksa harus menutup mata mereka demi menghindari virus misterius yang mengancam mereka. Bird Box pun membuka narasinya dengan langsung menghadirkan tragedi chaos yang langsung saja menyita perhatian saya. Saya yang awalnya hanya ingin melihat sekitar 15 menit di awalnya saja, seketika berniat untuk langsung melahap habis film produksi Netflix ini. Kalau di adegan awal nya saja sudah menghadirkan keseruan gila seperti itu, tentu saya akan mendapatkan hal lebih gila lagi di menit-menit sisanya. Dan sayangnya, keinginan tersebut berakhir dengan rasa yang sedikit kecewa karena di sisa menitnya, karena film dari Susanne Bier ini sama sekali tidak ada letupan konflik yang mampu menyaingi adegan chaos tersebut. Jangankan menyaingi, mendekati saja pun tidak.
Bier menyajikan dua cerita timeline yang berbeda. Yang pertama adalah perjuangan Malorie melakukan perjalanan dengan kedua anaknya ke suatu tempat, lalu yang kedua adalah cerita 5 tahun sebelumnya menceritakan kisah bertahan hidup Malorie dan Tom dimana Malorie yang saat itu masih dalam kondisi mengandung. Narasi yang kedua tentu diniati Bier untuk mengeksplorasi karakter Malorie serta pertemuannya dengan Tom yang merupakan love interest dari Malorie. Namun disinilah yang merupakan faktor terlemah Bird Box. Sama seperti The Purge (2013), potensi yang luar biasa menarik pada Bird Box tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh Bier.
Tempo film yang begitu tinggi di awal film tidak bisa dijaga oleh Bier. Praktis, setelah Malorie harus terjebak di dalam rumah yang dimiliki Greg (BD Wong), tensi film melambat tanpa adanya konflik yang berarti. Tidak ada perdebatan hebat yang terjadi antar penghuni yang bertahan hidup, tidak ada juga ancaman dari luar rumah yang membuat penonton menahan nafas. Ada satu momen yang sebenarnya bisa dimaksimalkan oleh Bier meletupkan konfliknya saat para karakter harus keluar dari rumah tersebut akibat persediaan makanan di dalam rumah telah menipis. Namun kembali, potensi tersebut dilewatkan saja. Andaikan saja Bird Box memiliki sutradara seperti Ari Aster yang memiliki visi luar biasa dalam menakut-nakuti penontonnya. Saya masih berharap bila di akhir film, Bird Box akan menghadirkan momen ending yang powerful layaknya Hereditary (my favorite movie this year), tetapi kembali, saya dikecewakan akan ending nya yang tampaknya diniati untuk membuka potensi sekuel film ini. Saya mencoba mencari tahu di internet apakah memang Bird Box versi novel memiliki akhir yang sama, dan kenyataannya versi novel dari Malerman memiliki ending yang lebih disturbing dibandingkan filmnya.
Naskah Bird Box yang ditulis oleh Eric Heisserer juga tidak memberikan ruang eksplorasi dalam terhadap karakter-karakternya sehingga saya tidak menyalahkan Anda jika Anda tidak terlalu perduli karakter selain Malorie dan Tom, bahkan untuk Tom sendiri masih kurang digali dengan dalam walau memang ada beberapa dialog didalamnya yang menceritakan tentang dirinya. Interaksi antar karakter minim sekali akan nuansa yang berwarna, seolah memang perbincangan yang terjadi tampak diniati sebagai pembunuh waktu. Satu-satunya faktor yang membuat saya cukup bertahan mengikuti Bird Box tidak lain tidak bukan adalah karena adanya John Malkovich yang memerankan Douglas berkat karakternya yang tidak bisa ditebak akan kelakuannya. Karakter Douglas juga terasa manusiawi dibandingkan karakter lainnya. Terdapat ambiguitas yang tersimpan, dan hal ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh baik oleh Heisserer.
Sandra Bullock jelas telah melakukan tugasnya dengan baik. Bullock adalah salah satu aktris yang memiliki kharisma likeable yang terpancar. Berkatnya, Malorie terlihat sebagai wanita yang tidak lemah walaupun memerankan karakter yang tengah mengandung. Bullock mampu menghidupkan setiap kalimat yang terlontar dari mulutnya. Hal tersebut terlihat di bagian ending nya yang cukup emosional berkat delivery dari Bullock. Sayang memang, Bullock tidak dimodali dengan naskah yang brilian. Bird Box jelas memiliki semua potensi yang bisa memberikan teror yang tak terlupakan kepada penonton, namun sekali lagi, Bird Box hanya berakhir sebagai film penghasil ide untuk kreator meme. Tidak jelek, tetapi tentunya bisa berakhir jauh lebih memuaskan dengan semua potensi didalamnya.