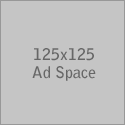"As a species we're fundamentally insane. Put more than two of us in a room, we pick sides and start dreaming up reasons to kill one another. Why do you think we invented politics and religion?"- Ollie
Plot
Kota kecil, Maine Town, secara tiba-tiba saja diserang kabut misterius. David Drayton (Thomas Jane) beserta putranya terjebak di dalam mall beserta penduduk lainnya. Pada suatu kejadian, David mengetahui jika didalam kabut tersebut, mereka ikut kedatangan tamu yang siap memangsa mereka.
Review
The Mist yang disutradarai oleh Frank Darabont ini, mungkin lebih dikenal disebabkan oleh endingnya. Walau memang endingnya merupakan aspek utama yang akan membuat The Mist susah terlupakan, namun secara keseluruhan, The Mist memiliki berbagai aspek positif yang mengantarkan film ini sebagai salah satu film alien invasion terbaik yang pernah saya saksikan.
Aspek terkuat yang membuat film yang diadaptasi dari novel Stephen King ini cukup spesial di mata saya adalah karena realistisnya Darabont dalam menggambarkan ketakutan-ketakutan dari warga Maine Town. Darabont menunjukkan jika karakter manusia yang sebenarnya akan terlihat kala berada dalam situasi yang mengancam nyawa mereka. Diperlihatkan disini penduduk yang terkurung dalam grocery store terbagi menjadi tiga yang diwakili oleh satu karakter masing-masing. Ada hardcore denial yang diketuai oleh Brent Norton (Andre Braugher), lalu David yang memilih berusaha sebisa mungkin untuk mencoba menyelamatkan diri, dan terakhir ada Mrs. Carmody (Marcia Gay Harden) yang berpendapat jika tragedi ini adalah hasil dari campur tangan Tuhan. Tinggal nantinya warga lainnya memilih berdiri di pihak mana, sesuai dengan apa yang mereka yakini demi bertahan hidup. Disinilah, bagi saya, pusat konflik dan sumber utama yang menyebarkan horor yang mengancam penduduk Maine Town yang terjebak.
Di tengah kesulitan yang menempatkan diri dalam posisi ujung tanduk, manusia akan menunjukkan diri sebenarnya demi bertahan hidup. Hal ini yang tampaknya ingin dieksplorasi oleh Darabont. Peristiwa kabut dan monster misterius yang terselubung di dalamnya, rupanya menjembatani akan tergerusnya kesabaran penduduk Maine Town yang terperangkap. Apapun dilakukan supaya bisa tetap menghembuskan nafas, tidak memperdulikan lagi nilai-nilai moral. Elemen ini jelas menimbulkan pertanyaan, siapa monster yang sesungguhnya?
Thomas Jane cukup baik dalam memerankan karakter alpha male, namun scene stealer dan paling membekas dalam benak penonton adalah karakter Mrs. Carmody yang diperankan secara menakjubkan oleh Marcia Gay Harden. Siapa yang sangka jika karakter ini nantinya lebih mampu memberikan ancaman bagi David dan kerabatnya. Penggambaran karakter nya pun cukup membantu, dimana ia cerewet, lalu tiap kata keluar dari mulutnya tidak jauh dari "konspirasi" agama. Yap, mudah sekali penonton untuk membencinya. Dengan ini juga membuktikan jika Gay Harden telah menunaikan tugasnya dengan brilian.
Oke, mari bicara tentang ending nya. Mungkin Stephen King menyukai ending yang diberikan Darabont. Tetapi saya pribadi, saya cukup kontra dan merasa ending nya hanya diniati Darabont supaya memberikan efek shocking, tanpa didukung dengan build up meyakinkan. Sehingga saya cukup mempertanyakan bagaimana mungkin si A tega melakukan "itu", meskipun bahaya mendekat. Ada janji yang terucapkan, namun apakah hal itu telah cukup kuat untuk melakukan tindakan nekat itu?
Terlepas dari kritik sebelumnya, saya tak bisa memungkiri jika Darabont menyajikan ending nya dengan apik sehingga meninggalkan bekas yang dalam di dalam pikiran penonton. Kita sebagai penonton, mungkin merasakan campur aduk dan bingung harus bereaksi seperti apa. Kesal? Kecewa? Merasakan kasihan setelah melihat raungan penyesalan dari David? Entahlah. Yang pasti, Darabont sukses menghadirkan sebuah adegan penuh ironis dan putus asa mendalam, dibantu lantunan The Host of Seraphim yang mengentalkan atmosfir tragis nya. Bukan salah Anda jika ending dari The Mist ini akan terpatri dalam di pikiran dan susah terlupakan.
Di tengah kesulitan yang menempatkan diri dalam posisi ujung tanduk, manusia akan menunjukkan diri sebenarnya demi bertahan hidup. Hal ini yang tampaknya ingin dieksplorasi oleh Darabont. Peristiwa kabut dan monster misterius yang terselubung di dalamnya, rupanya menjembatani akan tergerusnya kesabaran penduduk Maine Town yang terperangkap. Apapun dilakukan supaya bisa tetap menghembuskan nafas, tidak memperdulikan lagi nilai-nilai moral. Elemen ini jelas menimbulkan pertanyaan, siapa monster yang sesungguhnya?
Thomas Jane cukup baik dalam memerankan karakter alpha male, namun scene stealer dan paling membekas dalam benak penonton adalah karakter Mrs. Carmody yang diperankan secara menakjubkan oleh Marcia Gay Harden. Siapa yang sangka jika karakter ini nantinya lebih mampu memberikan ancaman bagi David dan kerabatnya. Penggambaran karakter nya pun cukup membantu, dimana ia cerewet, lalu tiap kata keluar dari mulutnya tidak jauh dari "konspirasi" agama. Yap, mudah sekali penonton untuk membencinya. Dengan ini juga membuktikan jika Gay Harden telah menunaikan tugasnya dengan brilian.
Oke, mari bicara tentang ending nya. Mungkin Stephen King menyukai ending yang diberikan Darabont. Tetapi saya pribadi, saya cukup kontra dan merasa ending nya hanya diniati Darabont supaya memberikan efek shocking, tanpa didukung dengan build up meyakinkan. Sehingga saya cukup mempertanyakan bagaimana mungkin si A tega melakukan "itu", meskipun bahaya mendekat. Ada janji yang terucapkan, namun apakah hal itu telah cukup kuat untuk melakukan tindakan nekat itu?
Terlepas dari kritik sebelumnya, saya tak bisa memungkiri jika Darabont menyajikan ending nya dengan apik sehingga meninggalkan bekas yang dalam di dalam pikiran penonton. Kita sebagai penonton, mungkin merasakan campur aduk dan bingung harus bereaksi seperti apa. Kesal? Kecewa? Merasakan kasihan setelah melihat raungan penyesalan dari David? Entahlah. Yang pasti, Darabont sukses menghadirkan sebuah adegan penuh ironis dan putus asa mendalam, dibantu lantunan The Host of Seraphim yang mengentalkan atmosfir tragis nya. Bukan salah Anda jika ending dari The Mist ini akan terpatri dalam di pikiran dan susah terlupakan.
7,75/10
"Painful memory is far more agonizing than pain in the heart"- Lee Sung-ho
Plot
Ahli patologi, Dr. Kang Min-ho (Kyung-gu Sol), diminta untuk melakukan autopsi terhadap gadis korban mutilasi yang ditemukan di daerah laut. Penyelidikan yang dilakukan oleh detektif Min Seo-Young (Hye-jin Han) pun berakhir dengan satu tersangka bernama Lee Sung-ho (Seung-bum Ryoo), seorang aktivis pembela lingkungan yang mengidap penyakit polio semenjak masih kecil yang memaksa dirinya harus berjalan dengan tongkat. Tanpa disadari oleh detektif Min, Lee Sung-ho memiliki rencana yang jauh lebih besar yang melibatkan Dr. Kang.
Review
Suatu kesalahan masa lalu bisa saja dilupakan, namun tidak ada jaminan apakah kita bisa terlepas sepenuhnya dari kesalahan tersebut. Dan kita juga tidak bisa menjamin balasan seperti apa yang akan diterima akibat dosa yang telah dilakukan. Sebagai pelaku, mungkin melupakan bukanlah hal yang sulit, namun bagaimana dengan pihak korban? Kim Hyeong-joon dengan film thriller nya yang sakit ini kemungkinan besar mampu membuat Anda untuk lebih berhati-hati lagi dalam melakukan suatu keputusan. Sebuah drama tragedi pembalasan dendam yang mengeksplorasi sisi gelap dalam diri manusia yang mampu membuat manusia bertransformasi menjadi sosok monster.
Di awal, No Mercy seolah mengarahkan bila kasus yang terjadi tidak lebih dari adalah aksi kriminal "biasa". Namun tidak butuh waktu lama, penonton akan sadar bila hal tersebut hanya sekedar kamuflase, karena seperti yang dibilang Inspektur Yoon (Ji-ru Sung), motif yang sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah murni dendam. Tidak salah memang bila penonton akan teringat pada film fenomenal yang juga dari Korea Selatan, Oldboy (2003). Fokus utama sama-sama berpusat akan dendam, dan tentunya pula twist ending nya yang mampu membuat kita bersumpah serapah. Dan kisah investigasi nya pun mengingatkan saya akan film The Chaser. Namun, bila dalam film tersebut tokoh utama nya telah berhasil menangkap satu tersangka, hanya tinggal mencari bukti kuat. Pada No Mercy, kita diberikan narasi sebaliknya. Di setengah jam awal, kita telah mengetahui siapa pelaku sebenarnya, yaitu Lee Sung-ho, bahkan detektif Min telah memiliki bukti yang cukup kuat untuk menjebloskan Lee Sung-ho ke jeruji besi. Lalu, apa yang membuat No Mercy menarik dan beda? Jawabannya ada pada story Dr. Kang. Disini Dr Kang malah dipaksa untuk sebisa mungkin mencari cara supaya pelaku utama tidak mendekam di penjara dengan cara mengaburkan segala bukti kuat yang telah ditemukan supaya Lee Sung-ho tidak ditangkap.
Narasi inilah yang merupakan daya tarik utama No Mercy. Menyaksikan bagaimana Dr. Kang mati-matian mensabotase bukti-bukti yang telah didapatkan tentu saja memberikan sajian thriller yang sangat menghibur. Narasi ini disajikan dengan tempo yang intens, diselingi pula dengan investigasi yang dilakukan oleh pihak polisi yang kebanyakan dilakukan oleh detektif junior, Min Seo-Young, yang sebaliknya ingin secepatnya menjebloskan Lee Sung-ho ke jeruji penjara. Rasa dilematis dari penonton pun ikut terbawa. Sulit membenarkan tindakan Dr. Kang, namun Dr. Kang pun berada di posisi yang tidak memiliki pilihan. Konflik batin pun semakin kental kala penonton akhirnya mengetahui alasan dibalik tindakan yang dilakukan Lee Sung-ho. Sehingga kita yang dari awal sepenuhnya mendukung Dr. Kang atau Detektif Min, berbalik memaklumi atas perbuatan Lee Sung-ho.
Twist ending nya pun semakin melengkapi tragedi dendam berdarah ini. Bagaimana rasa dendam yang telah mengakar begitu dalam mampu mematikan rasa manusiawi seseorang, sehingga mendorong untuk memberikan penghakiman sendiri yang dirasa setimpal. Entah terisnpirasi dari mana Hyeong-Joon bisa kepikiran untuk mengakhiri film nya ini dengan ending yang sakit seperti itu. Oh ya, untuk kalian yang memang memiliki kelemahan tersendiri dalam melihat darah, saya sarankan untuk tidak mencoba film ini karena seperti film-film thriller dari Korea Selatan lainnya, Hyeong-joon pun tidak sungkan-sungkan untuk menampilkan adegan-adegan berdarahnya. Bahkan adegan kala Dr. Kang melakukan autopsi pada mayat pun diperlihatkan terang-terangan oleh Hyeong-joon sehingga bukanlah keputusan yang bijak untuk menikmati film ini dengan menyantap makanan.
Twist ending nya pun semakin melengkapi tragedi dendam berdarah ini. Bagaimana rasa dendam yang telah mengakar begitu dalam mampu mematikan rasa manusiawi seseorang, sehingga mendorong untuk memberikan penghakiman sendiri yang dirasa setimpal. Entah terisnpirasi dari mana Hyeong-Joon bisa kepikiran untuk mengakhiri film nya ini dengan ending yang sakit seperti itu. Oh ya, untuk kalian yang memang memiliki kelemahan tersendiri dalam melihat darah, saya sarankan untuk tidak mencoba film ini karena seperti film-film thriller dari Korea Selatan lainnya, Hyeong-joon pun tidak sungkan-sungkan untuk menampilkan adegan-adegan berdarahnya. Bahkan adegan kala Dr. Kang melakukan autopsi pada mayat pun diperlihatkan terang-terangan oleh Hyeong-joon sehingga bukanlah keputusan yang bijak untuk menikmati film ini dengan menyantap makanan.
Hyeong-joon tentu telah melakukan pekerjaan yang brilian dalam mempresentasikan kisah pembalasan dendam ini. Walau memang masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki seperti cara menggulirkan narasinya yang kurang memperhatikan hal-hal detil sehingga menghasilkan beberapa pertanyaan yang sedikit mengganggu. Namun hal tersebut saya rasa bisa tertutupi oleh betapa menegangkannya jalinan cerita serta karakterisasi yang menarik pada masing-masing karakter. Dibantu pula dengan penampilan maksimal oleh pemeran-pemeran utamanya, terutama Kyung-go Sol yang secara meyakinkan memerankan Dr. Kang. Lihatlah transformasi nya dari Dr. Kang yang terlihat tenang diawal, menjadi orang yang seolah baru saja mengalami mimpi buruk. Rasa frustrasi nan putus asa begitu tergambar jelas dari ekspresi mukanya. Tentu juga twist ending nya yang susah dilupakan, membuat saya bertanya mengapa No Mercy seolah dibawah radar jika membicarakan film thriller terbaik dari negeri ginseng.