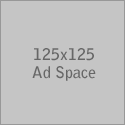"It has been said throughout the ages, that there can be no victory, without sacrifice."- Sir Edmund Burton
Plot
Keberadaan para Transformers yang selalu menghadirkan bencana bagi bumi memaksa pihak pemerintah meningkatkan kewaspadaan mereka. TRF (Transformers Reaction Force) yang dibentuk untuk merespon setiap kemunculan Transformers pun kini seolah tanpa pandang bulu menyerang Transformers yang terdeteksi keberadaannya, baik makhluk raksasa besi itu berada di pihak Autobot atau Decepticon. Cade Yeager (Mark Whalberg) yang telah berteman dengan tiap anggota Autobot memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya melindungi teman-temannya itu, sehingga dirinya pun kini menyandang status buronan dari pemerintah. Sang pemimping Autobot sendiri, Optimus Prime tengah "mudik" ke planet asalnya, Cybertron, untuk menemui dengan dewa di planet tersebut, Quintessa. Sementara grup Decepticon yang masih diketuai Megatron mengendus akan keberadaan tongkat terakhir yang dianggap sebagai poin penting terakhir untuk membawa Cybertron ke planet Bumi.
Review
Semenjak hadir pada tahun 2007 di dunia perfilman Hollywood, film-film Transformers bila dirunut dari segi kualitas penceritaan, tidak ada yang memuaskan sebenarnya, kecuali film perdananya yang harus diakui sangat menghibur. Itu pun dikarenakan pada film debut tersebut, penonton baik yang mengikuti Transformers versi kartunnya atau tidak, terhipnotis dengan segala transformasinya dari mobil ke robotnya yang digarap begitu sempurna. Momen ketika para Autobot menunjukkan jati diri mereka masih merupakan momen terbaik dalam franchise ini. Ceritanya juga masih berpusat pada rivalitas antara Autobot dan Decepticon sehingga walaupun mungkin tidak digarap dengan elegan, namun masih mudah dinikmati. Dan muncullah sekuel demi sekuelnya yang hanya berpusat pada adegan yang bombastis sehingga mengorbankan penceritaan. Magis yang saya sebutkan sebelumnya makin lama makin pudar, dan sang sutradara yang setia menggarap Transformers, Michael Bay, seolah semakin sulit untuk mengontrol dirinya dalam menyajikan action secquence nya. Penggunaan pada teknik cut yang terlalu banyak bukannya membantu aksi nya terlihat megah, malah merusak kenyamanan pada penonton. Dari Revenge of the Fallen hingga Age of Extinction, semuanya diserang habis-habisan oleh kritikus ataupun penonton kasual. Walau begitu, franchise Transformers tidak pernah gagal dalam mendulang keuntungan sehingga pihak Paramount tentu tidak perlu berpikir lebih panjang untuk tetap mempercayai Michael Bay dalam menggarap film-film Transformers, peduli setan penonton menanggapi hasil akhir nya seperti apa.
Bila Anda masih mempercayai bila Michael Bay akan berkaca pada hancur leburnya kualitas film-film Transformers selanjutnya dan berkenan untuk memperbaiki di sisi penceritaan, well, I fell bad for you. Segala formula dari film pertama hingga sekuelnya keempat kemarin masih digunakan Bay. Baik dari hal action, slow motion yang hadir di bagian aksinya, humor yang keseringan miss dibanding hit nya, serta visual efeknya yang harus diakui masih sangat memanjakan mata. Ya, visual efek dalam film Transformers mungkin hanya satu-satunya hal positif yang konsisten terjadi. Semuanya digarap dengan baik, terutama pertempuran terakhir kala semua karakternya berguling-guling di atas planet Cybertron. Tidak ada kesan menegangkan, namun tetap menghadirkan sisi excitement saat menyaksikannya. Yah, cukup ampuh untuk mengusir rasa kantuk yang telah menyerang saya pada 20 menit pertama.
Sebenarnya The Last Knight cukup menjanjikan pada awal-awalnya, terutama kala Bay yang dibantu Art Marcum dalam urusan menulis naskah kembali mempermainkan sejarah. Bila pada Dark of the Moon, Bay menyelipkan sejarah mendaratnya manusia di bulan untuk pertama kalinya, kali ini di The Last Knight, Bay mengaitkan kisah nya pada era medieval dimana terungkap bila Transformers sebenarnya telah menginjak daratan bumi kala itu. Lalu kemudian film bergerak ke zaman sekarang dan memperlihatkan kehidupan para Transformers yang mulai kehilangan tempat di bumi dan malah dianggap sebagai suatu ancaman bagi pemerintah. Tidak lama dari itu, telah diperlihatkan satu robot yang tewas seketika akibat serangan dari TRF. Dari sini saya yang sama sekali buta karena tidak melihat satu kalipun trailer film ini, mulai melihat suatu potensi cerita yang bisa dibilang fresh. Memang, Age of Extinction memiliki fondasi cerita yang tidak jauh berbeda, bahkan bisa dikatakan sangat mirip. Namun, kematian salah satu robot di awal cerita memiliki hubungan khusus dengan supporting character nya, yaitu Izabella (Isabella Moner). Imajinasi saya mulai liar dengan membayangkan akan terjadinya konflik internal antara manusia dan Transformers. Terutama kala Bumble Bee bersama Cade berkonfrontasi langsung dengan TRF, yang menghadirikan momen-momen mengejutkan, yaitu kembalinya Lennox (Josh Duhamel) dan atraksi Bee mengenai kemampuan barunya yang digarap brilian oleh Bay. Namun sayang, segala kesenangan itu semakin pudar kala Bay kembali memusatkan konfliknya pada akhir dunia yang diturut campuri oleh para Transformers yang berbeda keyakinan dengan Autobot.
Dari awal film, bila Anda perhatikan, fokus penceritaan Transformers memang tidak pernah jauh dari usaha pihak Decepticon untuk mengambil alih dunia dan memindahkan planet Cybertron ke bumi. Transformers sangat butuh penyegaran ide cerita, maka ketika saya mengetahui arah penceritaan akan berujung kesana, rasa minat menonton film ini mulai kendur dari menit demi menit The Last Knight berjalan. Semakin diperparah pula dengan interaksi antar karakternya yang sama sekali tidak ada yang memorable. Momen perbincangan antar anggota Autobot yang diniati sebagai ajang perkenalan kepada penonton malah berakhir membosankan akibat rentetan dialognya yang sangat dipaksakan untuk terlihat lucu. Padahal bila saja tiap signature antar anggota dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin, niat tersebut akan berakhir dengan maksimal. Bay juga kembali kurang cerdik dalam memanfaatkan karakter barunya seperti Izabella yang hampir sama sekali tidak memiliki esensinya dalam perkembangan cerita. Yang menyedihkan lagi adalah keberadaan para Decepticon yang semakin tergeser dari sosok pengancam dunia beralih ke tokoh yang tidak ada bedanya sebagai cheerleader. Sempat terbersit pemikiran bila Decepticon akan memegang peranan besar kala setiap anggotanya mendapatkan perkenalan yang bisa dibilang cukup spesial. Namun sayang, ternyata momen-mome tersebut hanya digunakan untuk memperpanjang durasinya karena tidak lama kemudian keberadaan mereka sudah terlupakan sama sekali. Melihat Megatron yang semakin kehilangan aura menakutkannya jelas merupakan kesedihan besar bagi saya.
The Last Knight sedikit kembali merebut atensi kala Cade Yeager mengunjungi Inggris. Kehadiran Laura Haddock dan Sir Anthony Hopkins sangat berpengaruh dalam menjaga mata saya untuk tetap terpaku kepada layar. Interaksi mereka dengan Cade cukup berhasil dan mengalir lancar. Hopkins jelas merupakan yang terbaik diantara Mark dan Laura. Sebagai Edmund Burton, Hopkins menyuntikkan energi yang berlipat setiap kali dirinya tampil di layar. Laura Haddock pun tampaknya berhasil menjadi pemeran wanita terbaik di franchise Transformers. Fisiknya jelas tidak kalah jauh dari Megan Fox dan bila membicarakan akting, tentu Laura berada di atas jauh meninggalkan Fox. Dan yang paling penting, Laura jauh mudah disukai. Mark Wahlberg pun jelas tanpa kesulitan dalam menghadirikan sosok action hero, dan Mark juga memiliki kapabilitas dalam melontarkan one liner yang sebenarnya tidak terlalu lucu, namun berkat ekspresi muka serta nada suaranya yang pas membuat one liner tersebut bekerja. Perhatikan saja saat Cade melontarkan kata "what?" di adegan yang melibatkannya bersama karakter Jimmy (Jerrod Carmichael). Oh, lupa juga bagaimana robot C-3PO palsu bernama Cogman yang sangat mencuri perhatian berkat kepribadiannnya yang menarik serta mampu meletupkan berbagai humor yang kebanyakan berhasil dari dirinya. Praktis keberadaan Cogman cukup ampuh dalam mengobati rasa rindu penonton terhadap pemimpin Autobot, Optimus Prime yang harus menyingkir hingga akhirnya kembali lagi pada saat narasi film bergerak menuju akhir. Tidak terpungkiri memang, magnet yang dihadirkan Prime masih sulit untuk tergantikan hingga saat ini.
Memang untuk mudah dalam menikmati film-film Transformers tergantung dari ekspektasi yang Anda pasang sebelum menonton. Jangan terlalu memperhatikan detil demi detil cerita karena itu akan sangat mengganggu kenikmatan kalian saat menonton. Bila mau membicarakan plot hole, jelas The Last Knight memiliki banyak sekali. Saya menonton The Last Knight bersama teman saya yang belum pernah menyentuh sekalipun dengan film-film Transformers selanjutnya. Dan hasilnya beberapa kali dirinya protes dengan ketidakjelasan yang hadir, sehingga saya hanya menjawab "ini Transformers, bro. Santai". Bagi saya, ini sama sekali tidak ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya dan melewatkan suatu potensi yang bisa berfungsi untuk menyegarkan penceritaan. Hanya sedikit momen-momen yang bisa diingat, dan karena Transformers:The Last Knight memiliki durasi 2 jam lebih, bayangkan betapa tersiksanya dalam bioskop bagi yang tidak bisa menikmati Transformers: The Last Knight.