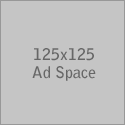"Sucess doesn't come for free, Miguel. You have to be willing to do whatever it takes to.. seize your moment. I know you understand."- Ernesto de la Cruz
Plot
Miguel memimpikan menjadi musisi sehebat idolanya, Ernesto de la Cruz. Namun, akibat dari sejarah turun temurun keluarganya, Miguel hidup dalam keluarga yang sangat membenci musik dikarenakan nenek moyang sekaligus pendiri bisnis sepatu yang kini tetap diteruskan oleh keluarga besar Miguel, Mama Imelda membenci sang suami yang meninggalkannya dan anak semata wayang mereka, Coco, demi mengejar impian menjadi musisi yang mengakibatkan pula rasa benci itu menular pula kebenciannya terhadap musik. Meski dilarang keras, terutama oleh sang nenek, Abuelita, Miguel terus mengejar impiannya. Dan ia merasakan jika kompetisi musik Dia de Muertos adalah momentum untuk dirinya dalam rangka pembuktian kepada seluruh keluarganya bila ia memang ditakdirkan untuk menjadi musisi.
Review
Dengan proyek seperti The Incredibles 2 yang akan hadir tahun ini serta Toy Story 4 yang masih sebatas rumor kemunculannya, Pixar memang seolah terkesan akan minim kreasi. Tetapi anggapan itu seketika musnah kala Inside Out muncul 2 tahun lalu. Hadirnya film yang berhasil membuat saya beberapa kali meneteskan air mata tersebut benar-benar menjadi bukti jika para kreator yang bekerja di Pixar masih tetap memiliki kapabilitas dalam mempermainkan emosi para penontonnya, termasuk pria dewasa yang harus bernasib seperti saya kala mereka pun turut dipaksa untuk menyapu air mata di pipi. Pixar sepertinya ingin menjaga momentum tersebut sampai The Incredibles 2 akan rilis nanti dengan menghadirkan kisah seorang bocah berusia 12 tahun mengejar mimpinya untuk hidup dalam dunia musik dalam balutan judul film bernama Coco.
Jika dalam Inside Out kita dibawa kembali untuk mengingat kepingan-kepingan kenangan indah pada masa kecil, Coco membawakan tajuk yang tidak terlalu jauh sebenarnya dari topik tersebut karena masih bersinggungan dengan keluarga, dengan membawakan pertanyaan bagaimana bila kita benar-benar dilupakan setelah roh tidak lagi berada di dalam raga ini. Ide cerita itu belum terlalu menyeruak karena di awal-awal film berjalan, sang sutradara sekaligus penulis naskah, Lee Unkrich, mengajak penonton untuk mengenal lebih dekat mengenai Miguel dan keluarga nya yang sangat membenci musik.
Pada momen ini, Coco menawarkan formula seperti film Up yang terasa begitu realistik dengan kehidupan nyata untuk takaran film animasi, dengan meniadakan elemen-elemen imaji seperti mainan yang bisa bergerak sekaligus berbicara, ataupun dunia emosi yang terdapat dalam tubuh manusia, Walaupun begitu, atensi saya telah terengkuh karena satu kata saja, dan satu kata tersebut adalah musik. Karakter utamanya bagaikan mewakili sebagian besar anak-anak kecil yang memimpikan hal yang sama seperti Miguel, untuk menjadi musisi yang hebat dan mampu diidolai serta dicintai oleh para penggemarnya. Hal itu tentu saja didasari oleh faktor untuk mengikuti jejak langkah sang idola. Saya begitu mengagumi John Lennon dan Kurt Cobain (I wish I meet them at afterlife) sehingga mimpi saya yang masih terpendam hingga saat ini adalah menjadi musisi sehebat mereka, dan hal itu pula yang ingin diwujudkan oleh Miguel. Namun, hidup dengan keluarga yang justru bertentangan dengan impiannya tersebut, tentu tidak mudah untuk Miguel mewujudkannya. Apakah impian tersebut sangat berharga jika kita harus bertentangan dengan keluarga? Bukankah Keluarga adalah segala-galanya? Pertanyaan ini terus menghinggapi di benak saya sehingga saya meyakini petualangan yang disajikan oleh Unkrich dalam Coco akan penuh dengan petualangan yang emosional.
Dirasakan cukup untuk panggung "real world" nya, Unkrich pun menyimpan kejutan untuk para penonton yang tidak menyaksikan trailer ataupun tidak mengetahui materi promosi maupun marketing film Coco. Unkrich serta para kreator Pixar telah menyiapkan panggugn yang sebenarnya yaitu dunia yang bernama The Land of Dead. Nama tersebut memang tidak indah di dengar, namun pikiran itu hadir jika kita belum melihat bagaimana Unkrich dkk. sebenarnya menciptakan sebuah dunia yang begitu indahnya dengan segala pameran warna yang sangat memanjakan mata. Bahkan, jembatan yang ditaburi jutaan kelopak bunga Mexican Marigold saja ditampilkan sedemikian indahnya, dan mungkin jembatan ini menjadi salah satu elemen favorit saya akan film ini. Visualisasi yang tidak hanya megah namun juga membuktikan jika para kreator Pixar memiliki imajinasi yang luar biasa.
Kehebatan Pixar lainnya adalah bagaimana menyajikan sebuah cerita mengenai coming of age yang terasa dewasa, menyentuh, dan juga dekat dengan penonton, walaupun melibatkan berbagai hal yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Coco pun memiliki hal-hal tersebut, dimana pertanyaan mengenai kapan sebenarnya manusia akan merasakan kematian yang sebenarnya di bawa ke permukaan. Jika kalian penggemar animanga One Piece, pasti kalian masih mengingat dialog yang di ungkapkan oleh Doctor Hiluluk.
When do you think people die? When they are shot through the heart by the bullet of a pistol? No. When they are ravaged by an incurable disease? No. When they drink a soup made from a poisonous mushroom!? No! It’s when... they are forgotten.
Pedih sekali rasanya jika tidak ada seseorang pun mengingat akan eksistensi kita. Sedih sekali rasanya jika keluarga kita pun tidak pernah menyebutkan nama kita dalam perbincangan di tengah keluarga. Di balik indahnya The Land of Death, terdapat sekumpulan "orang" yang terasing akibat foto mereka tidak dipajang dimanapun, salah satunya adalah Hector yang nantinya memiliki pengaruh besar dalam pencarian jawaban yang tengah dilakukan oleh Miguel. Dan bagi mereka yang juga hilang dalam ingatan orang yang masih hidup di dunia, arwah mereka pun akan hilang dari The Land of Death, yang berarti mereka telah merasakan kematian yang sesungguhnya. Scene "the final death" yang hadir di pertengahan cerita itu saja telah menunjukkan piawainya Unkrich meramu sebuah adegan yang memiliki gabungan unsur seperti ketenangan, keindahan dan kesedihan yang tidak saya duga-duga akan datang. Dan air mata saya hampir menetes untuk karakter yang hanya hadir untuk 5 menit saja! Dan masih sempatnya pula Unkrich mampu menghadirkan momen penggelak tawa di tengah adegan yang cukup emosional tersebut.
Fondasi cerita Coco begitu kuat, sehingga twist yang hadir saat film telah menyentuh 1 jam pun tidak hanya mengejutkan dan membelokkan cerita, namun juga memiliki sebuah jawaban yang ironi. Ya, ironi karena apa yang kita harapkan dan impi-impikan dari sang idola maupun panutan tidak selamanya berjalan selaras dengan kenyataan (dan Kevin Smith memiliki pengalaman tersebut). Unkrich memperlihatkan bagaimana kejamnya dunia hiburan yang lekat dengan unsur plagiarism nya yang turut berpengaruh besar pada eksistensi seorang individu.
Mungkin Coco tidak memiliki kisah petualangan yang hebat seperti trilogi Toy Story, Up maupun Inside Out. Tetapi petualangan mencari jati diri milik Miguel dibingkai dengan aspek emosional yang rasanya mustahil untuk tidak ikut terbawa dalam mengikuti sepak terjang Miguel. Pixar pun secara konsisten menghadirkan karakter demi karakter yang menarik, dengan Miguel sebagai penggerak roda cerita dan tentunya Hector yang menjadi favorit saya disini. Love-hate relationship hadir singkat setelah momen twistnya disertai dengan karakter tsundere dari Mama Imelda pun begitu efektif dalam memicu gelak tawa dan gemas penonton. Dilengkapi dengan lagu emosional "Remember Me", rasanya cukup mustahil pula untuk para kompetitor menyaingi kedigdayaan Coco di Academy Awards dalam kategori Best Animated Feature.