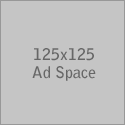"Number 11 my ass!!"- Roman
Plot
Bulan madu yang dilakukan Dominic Toretto (Vin Diesel) bersama Letty (Michelle Rodrigues) harus terganggu dengan kehadiran wanita misterius bernama Cipher (Charlize Theron) yang menginginkan Toretto membantu ambisinya. Toretto yang jelas pada awalnya menolak ajakan Cipher akhirnya bersedia membantu Cipher setelah melihat kartu as yang dimiliki Cipher, walau harus memaksa dirinya untuk berhadapan dengan anggota-anggota keluarganya yang telah ia bangun sejak lama. Ya, untuk pertama kalinya, Toretto berada di sisi berlawanan dengan keluarganya.
Review
Dari sekian banyak permasalahan yang dimiliki The Fast and The Furious franchise, salah satu masalah utama yang mengganggu saya adalah terlalu overpowered nya tim yang dimiliki Dominic Toretto. Problem tersebut sedikit tertutupi dengan kehadiran Luke Hobbs-nya Dwayne Johnson sebagai pihak yang menjadi lawan seimbang bagi Toretto, tetapi itu hanya cukup berlaku bagi Toretto seorang diri, karena apabila membicarakan keseluruhan tim, yang dimiliki Luke Hobbs tetaplah tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Toretto. Permasalahan ini pun semakin menjadi-jadi kala Hobss yang awalnya merupakan lawan bertransformasi menjadi aliansi dan anggota baru dalam Toretto's family, sehingga setiap lawan yang muncul di tiap-tiap film sesudah Fast Five, sama sekali tidak ada intimidasi yang meyakini penonton tim Toretto akan kesulitan menghadapi tiap musuh baru yang harus dihadapi. Dan tampaknya F. Gary Gray menyadari celah besar ini sehingga dengan bantuan Chris Morgan dan Gary Scott Thompson, Gary Gray mendapatkan inovasi baru untuk tetap membuat franchise ini terasa fresh. Inovasi tersebut adalah memposisikan karakter utamanya itu sendiri yaitu Toretto sebagai pihak antagonist nya.
Memang, bagi yang mengikuti franchise ini dari film pertamanya mudah saja menyadari pasti ada alasan di balik membelotnya Toretto yang sekarang malah justru tega harus berhadapan dengan tiap anggota keluarganya. Namun tak dipungkiri ide ini merupakan daya tarik utama yang mau tidak mau para fans yang telah merasakan kewalahan mengikuti franchise ini tetap merasa tergoda untuk kembali menyicipi The Fate of the Furious. Keberadaan Toretto di posisi lawan sangat membantu sang villain utama, Cipher, terasa intimidatif selain dengan kemampuan hacker nya yang berada di atas Ramsey. Charlize Theron pun merupakan pilihan yang tepat untuk memerankan Cipher yang manipulatif, tenang namun meyakinkan melalui penghantaran kata-katanya yang terasa lembut dan tidak terlihat lemah walau harus dikelilingi oleh pria-pria berotot besar. Namun sayang sekali kala Gary Gray berhasil menutupi lubang kelemahan yang saya ungkap di awal paragraf, Gary Gray malah tetap mengulangi kekurangan lainnya, yaitu kurangnya pendalaman pada villain utama. Maksud saya, lihat Cipher, apa yang mengharuskan dirinya melakukan semua tindakan kriminal yang ada? Siapa sebenarnya Cipher? Bagaimana dirinya memiliki semua sumber daya yang mungkin mampu menyaingi sumber daya yang dimiliki badan keamanan suatu negara? Dan dari semua orang hebat di dunia, mengapa dia sangat membutuhkan bantuan Dom? Mungkin kalian menganggap saya terlalu berlebihan untuk memikirkan itu semua, tapi mau bagaimana lagi, karakterisasi yang dangkal pada Cipher ini cukup mengganggu saya dalam menikmati The Fate of the Furious. Okay, logika memang harus dimatikan kala menyaksikan adegan aksinya, tetapi berkenaan dengan karakter, hal tersebut tidaklah berlaku.
Oh, mengenai actionnya yang merupakan jualan utama dari franchise ini sehingga mampu bertahan hingga ke instalmen ke delapan, percayalah The Fate of the Furious masih memiliki momen-momen aksi yang sangat menghibur. Memang tidak ada yang mampu menyaingi action secquence yang melibatkan brankas di Fast Five, tetapi aksi-aksi yang masih melibatkan kendaraan roda empat ini tetap terasa bombastis dengan efek kejut di tiap adegan aksi terjadi, tidak ada contoh yang lebih baik menjelaskan ini selain melihat apa yang terjadi di adegan kejar mengejar di secquence terakhir dengan melibatkan kapal selam raksasa. Namun bila membicarakan favorit, saya lebih memilih secquence di pertengahan durasi kala Cipher melibatkan puluhan mobil di jalanan maupun di garasi gedung untuk melancarkan agendanya. Entah berapa kali ucapan "holy shit" yang saya keluarkan untuk mengekspresikan kekaguman saya apa yang ditampilkan Gary Gray disini. Tidak ketinggalan juga Gary Gray tetap menyelipkan beberapa humor terlontar dari, siapa lagi kalau bukan interaksi antara Tej Parker dan Roman, walau dosisnya serasa ditahan disini. Sayang memang dari sekian film yang telah ditelurkan pada franchise ini, dua karakter yang sebenarnya salah satu alasan bagi saya untuk selalu merasa terhibur menyaksikan film-film The Fast and the Furious (terutama Roman, damn, komentar dia saat ia ketahui bahwa dirinya tidak masuk interpol's top ten most wanted list sukses meledakkan tawa saya) diposisikan hanya sekedar sebagai comic relief dan tidak memiliki momen-momen yang menjadi highlight untuk mereka selain humor-humor yang mereka lontarkan.
Dengan mengutamakan adegan-adegan aksinya, tampaknya Gary Gray harus mengorbankan untuk pendalaman cerita yang sebenarnya kala memposisikan Toretto sebagai tembok penghalang bagi keluarga yang ia miliki, banyak sekali sub plot yang bisa digali, apalagi saat terungkap mengenai motif yang mendorong Toretto untuk bersedia membantu Cipher. Namun karena memang franchise ini daya jualnya adalah dengan melihat para karakternya beraksi di belakang setir mereka ataupun baku hantam antar karakternya, potensi tersebut hanya terlewat begitu saja. Selain itu kesempatan emas yang Gary Gray lepaskan juga adalah tidak lebih memperbanyak interaksi antara Hobbs dan Deckard yang secara mengejutkan ternyata sangat menghibur dan seringkali merebut spotlight.
Sekali lagi, mungkin bagi kalian saya terlalu menganggap serius dalam mengamati berbagai aspek dalam The Fate of the Furious, namun apabila memang franchise ini ingin menawarkan sesuatu yang baru, sebaiknya pihak Universal harus berani lebih memperhatikan sektor cerita dan tidak hanya melulu menceritakan Dominic Toretto, karena apabila hanya mengandalkan aksi kendaraan roda empatnya saja, bukan tidak mungkin penggemar setia franchise The Fast and the Furious merasakan kebosanan, hingga mengharuskan franchise The Fast and the Furious benar-benar berada di finish line.